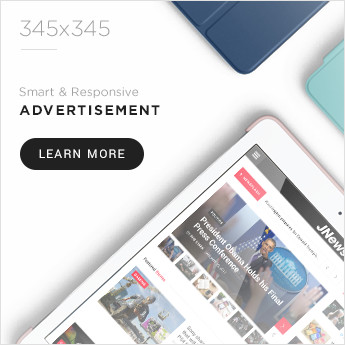MabesNews.tv, Tanjungpinang – Situasi politik dan sosial di Kepulauan Riau kian dinamis menjelang Hari Jadi Provinsi pada 24 September 2025. Aliansi Gerakan Bersama Rakyat Kepri resmi menyatakan akan menggelar aksi besar di Gedung DPRD Kepri dan melanjutkannya ke Kawasan Tepi Laut Tanjungpinang. Aksi ini bukan sekadar perayaan momentum politik, melainkan bentuk perlawanan terhadap rencana pemerintah provinsi yang akan melelang pengelolaan Kawasan Gurindam 12. Kebijakan tersebut dianggap mengancam hak publik, mengkomersialisasi ruang sosial, dan menutup akses masyarakat terhadap salah satu ikon kota yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas.
Sebelum aksi berlangsung, aliansi menjadwalkan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan beragam elemen masyarakat. Mereka menegaskan pentingnya forum diskusi yang terbuka, bebas dari nuansa politik elitis. Rapat Dengar Pendapat (RDP) diminta tidak dilakukan di ruang Ketua DPRD yang dinilai sarat simbol kekuasaan, melainkan di ruang netral agar proses dialog tidak menimbulkan kesan dominasi pihak tertentu. Aliansi juga menuntut keterlibatan langsung pihak pengelola Gurindam 12, Dinas PUPR, serta Komisi I, II, dan III DPRD Kepri untuk memberikan klarifikasi menyeluruh mengenai arah kebijakan pengelolaan kawasan tersebut.
Bagi masyarakat Tanjungpinang, Gurindam 12 bukan sekadar ruang publik, melainkan simbol identitas budaya dan ruang interaksi sosial lintas generasi. Wacana pelelangan yang berpotensi memberi jalan bagi investor swasta dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap esensi ruang terbuka yang semestinya menjadi milik rakyat. Kekhawatiran publik menguat bahwa bila ruang tersebut jatuh ke dalam pengelolaan komersial, maka yang terjadi adalah eksklusivitas dan pembatasan akses bagi kelompok-kelompok masyarakat kecil yang selama ini menjadikan kawasan itu sebagai ruang rekreasi, kegiatan seni, maupun aktivitas ekonomi informal.
Pakar tata kota sekaligus akademisi yang meneliti hubungan ruang publik dengan tata kelola pemerintahan mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini rawan menimbulkan dampak jangka panjang. Ia menegaskan bahwa ketika ruang publik diprivatisasi, orientasi keuntungan akan mengalahkan fungsi sosial. Hal ini dapat memicu marginalisasi, di mana masyarakat kecil terpinggirkan dari ruang interaksi mereka sendiri. Menurutnya, pemerintah justru seharusnya memperkuat pengelolaan berbasis pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. “Komersialisasi ruang publik sama artinya dengan menggadaikan masa depan masyarakat. Kota kehilangan jantung sosialnya ketika ruang-ruang bersama diubah menjadi arena bisnis,” tegasnya.
Pengamat kebijakan publik menambahkan dimensi lain dalam kritiknya. Ia menilai Gurindam 12 memiliki peran strategis sebagai “paru-paru sosial” Tanjungpinang, sebuah simbol keseimbangan antara ruang hidup warga dan pertumbuhan kota. Ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memperlakukan ruang publik, sebab kesalahan kebijakan bisa memicu konflik horizontal. “Ketika ruang terbuka dipasung dengan aturan tarif atau pembatasan akses, pemerintah pada dasarnya sedang membangun tembok pemisah di tengah masyarakat. Itu bukan hanya merusak tatanan kota, tetapi juga bisa menyalakan api perlawanan,” katanya.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, sejumlah pakar menilai bahwa kebijakan pelelangan pengelolaan ruang publik mengindikasikan lemahnya orientasi pelayanan publik di tingkat daerah. Ada kecenderungan menjadikan aset publik sebagai sumber pendapatan jangka pendek melalui mekanisme komersial, ketimbang membangun tata kelola yang berkelanjutan. Model seperti ini, menurut mereka, mencerminkan pendekatan administratif yang pragmatis namun berisiko mengorbankan kepentingan jangka panjang masyarakat.
Selain itu, persoalan ini juga membuka perdebatan mengenai paradigma pengelolaan wilayah kota. Apakah ruang publik diposisikan sebagai bagian dari layanan sosial yang harus dijamin negara, ataukah sebagai instrumen ekonomi yang dapat dilelang demi pemasukan? Bagi banyak pemerhati tata kelola, pilihan pemerintah untuk membuka peluang komersialisasi menunjukkan bias kebijakan yang lebih condong pada pasar ketimbang pelayanan rakyat.
Rencana aksi pada Hari Jadi Provinsi Kepri menjadi titik kulminasi dari gelombang kritik tersebut. Aliansi Gerakan Bersama Rakyat Kepri menegaskan bahwa aksi ini adalah simbol perlawanan terhadap tata kelola daerah yang dianggap elitis, tertutup, dan jauh dari aspirasi rakyat. Mereka ingin mengingatkan bahwa ruang publik tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas, melainkan hak melekat masyarakat yang harus dijaga sebagai bagian dari demokrasi ruang kota.
Banyak pihak menaruh harapan agar FGD dan RDP yang direncanakan tidak berhenti pada seremoni formalitas, melainkan benar-benar membuka pertarungan ide dan arah kebijakan. Transparansi, keterlibatan masyarakat, serta pelestarian nilai budaya Gurindam 12 menjadi garis merah yang tidak boleh dilewati pemerintah daerah.
Gelombang kritik yang semakin deras menunjukkan bahwa Gurindam 12 telah bertransformasi dari sekadar kawasan publik menjadi simbol perjuangan mempertahankan hak kolektif masyarakat atas ruang hidup mereka. Jika suara rakyat kembali diabaikan, tidak menutup kemungkinan Gurindam 12 akan menjelma menjadi titik api perlawanan baru terhadap wajah pemerintahan yang kian dianggap menutup diri dan terjebak dalam logika komersialisasi ruang.
arf-6