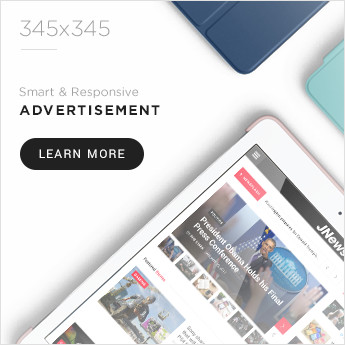Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Inteliijen)
Mabesnews.tv, -DALAM politik, yang tampak di permukaan seringkali hanyalah kulit tipis dari manuver intelijen yang bergerak di bawah tanah. Sun Tzu dalam The Art of War menuliskan“All warfare is based on deception.” Perang politik pun demikian. Apa yang kini kita saksikan dimana penempatan Gibran sebagai wakil presiden, loyalis Jokowi di kabinet, hingga aksi demonstrasi kolosal, bisa dibaca sebagai tahapan berlapis dari “operasi garis dalam” Jokowi.
Samuel Huntington, dalam Political Order in Changing Societies, mengingatkan bahwa negara dengan institusi lemah mudah tersandera oleh kekuatan informal. Indonesia pasca Jokowi persis berada di titik rawan itu. Dengan memanfaatkan kelengahan presiden baru, Jokowi terlihat menanam pengaruh di dua ranah struktural dan psikologis. Secara struktural lewat kader-kader yang mengisi pos menteri dan aparat keamanan, sementara secara psikologis lewat narasi bahwa Prabowo gagal memenuhi janji.
Tahap kedua operasi garis dalam mengingatkan pada konsep Clausewitz tentang “center of gravity” dimana titik pusat kekuatan lawan yang harus dilemahkan. Bagi Jokowi, titik itu adalah legitimasi Prabowo di mata rakyat. Blunder-blunder kebijakan dari menteri loyalis Jokowi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari desain untuk mengikis kepercayaan publik. Setiap janji Prabowo diubah menjadi jebakan, dimana semakin ia gagal mewujudkan, semakin kuat narasi oposisi bahwa presiden hanya pandai bicara.
Tahap ketiga mengandalkan teknologi dengan media sosial sebagai force multiplier. Operasi psikologis (PSYOPS) dipraktikkan dengan rapi, memobilisasi opini publik hingga menciptakan kesan negara dalam krisis. Paul Linebarger dalam Psychological Warfare menuliskan bahwa propaganda paling efektif adalah yang memanfaatkan luka batin rakyat. Maka isu korupsi, kemiskinan, dan represifitas aparat diangkat bukan sekadar protes, tetapi sebagai bahan bakar gerakan massa. Demonstrasi lalu dipicu agar tampak anarkis, bentrok dengan aparat pun diatur seperti sandiwara, untuk menyebar kesan presiden kehilangan kendali.
Tahap keempat adalah fase paling berbahaya yaitu penguasaan penuh atas people power. Inilah skenario “decapitation without coup” atau kudeta tanpa kudeta. Jika Jokowi berhasil mengendalikan massa dan aparat sekaligus, maka 2029 hanyalah formalitas dan dinasti kembali berkuasa. Guillermo O’Donnell menyebutnya delegative democracy, demokrasi yang direduksi menjadi otoritarianisme elektoral.
Pertanyaannya, apa risiko bagi bangsa? Jika skenario garis dalam dibiarkan, Indonesia bisa tergelincir menjadi failed state pada 2035. Bukan karena invasi asing, tetapi oleh erosi kepercayaan publik dan dominasi satu dinasti yang mengebiri institusi. Seperti Yugoslavia pada 1990-an, negara bisa runtuh dari dalam oleh ambisi elite yang tak terkendali.
Aksi anarkis 25-28 Agustus 2025 menjadi tanda. Bukan hanya rakyat muak pada aparat yang represif, tetapi Polri sendiri kehilangan legitimasi. Setiap pukulan polisi pada demonstran bukan sekadar tindakan keamanan, melainkan amunisi propaganda bagi garis dalam. Seperti kata Machiavelli dalam The Prince yang berbunyi “The arms by which a prince defends himself, if turned against him, will be his ruin (Senjata yang digunakan seorang pangeran untuk membela diri, jika digunakan untuk melawannya, maka akan menjadi kehancurannya).
Di sinilah dilema Prabowo. Apakah ia tetap tampil gemoy dan lentur, atau kembali keras kepala seperti yang dulu membuat rakyat percaya? Untuk melawan operasi garis dalam, presiden perlu strategi kontra intelijen dengan mengganti Kapolri yang dianggap centeng Jokowi, merombak kabinet dari kroni berwajah ganda, dan membangun ulang kepercayaan publik.
Dalam literatur intelijen, ini disebut counter intelligence operation dengan memutus rantai infiltrasi lawan sebelum mereka menguasai panggung. Tanpa itu, presiden hanya akan menjadi wayang di tangan dalang lama.
Sejarah mengajarkan bahwa Soekarno tumbang karena tersandera PKI dan militer; Soeharto jatuh oleh gelombang massa yang awalnya ia abaikan. Prabowo kini berada di persimpangan yang sama. Apakah ia memilih menjadi presiden yang terseret arus operasi garis dalam, atau pemimpin yang menutup pintu dinasti dengan tegas?
Rakyat tidak menunggu Prabowo yang gemoy. Rakyat menunggu Prabowo yang keras kepala, yang berani menampar balik operasi garis dalam dengan tindakan nyata. Sebab dalam politik, seperti kata Clausewitz, perang sejatinya hanyalah kelanjutan politik dengan cara lain. Dan bagi Jokowi, politik hanyalah kelanjutan dinasti dengan skenario garis dalam. (Samsul Daeng Pasomba/Tim)